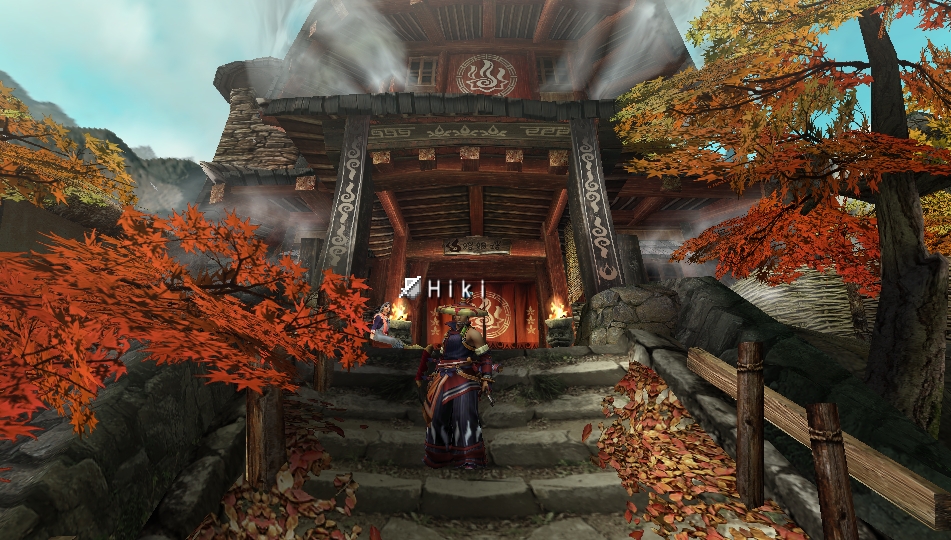Suka Duka Belajar di Singapura
Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata “Singapura”?
Mungkin sebagian besar orang akan berkata: Changi Airport, kota yang bersih, Orchard Road, atau bahkan surga belanja.
Namun buat saya tak demikian.
Belasan tahun yang lalu, Singapura adalah rumah sekaligus tempat menimba ilmu.
Saat SMA, saya memberanikan diri untuk mendaftar program pertukaran pelajar ke luar negeri. Tak disangka-sangka, saya pun diterima oleh salah satu sekolah di Singapura untuk menimba ilmu selama setahun penuh. Tak pikir panjang, saya pun menerimanya.
Beberapa bulan setelah pengumuman tersebut, saya pun berangkat ke Singapura bersama 30 orang lainnya, yang mungkin adalah putra-putri terpilih bangsa (tidak termasuk saya, tentunya). Selama hampir dua jam di pesawat, banyak dari kami terlihat sumringah, serta wajah berseri-seri, penasaran seperti apa rasanya belajar di Singapura nantinya.
Setelah saya mendarat di bandara Changi yang bersih nan wangi, saya pun langsung diantar ke tempat tinggal saya selama satu tahun ke depan, dan setelahnya saya coba mengeksplorasi tempat di sekitar saya tinggal.
Lalu beberapa hari kemudian, hari saya bersekolah di Singapura pun tiba.
Saya ditempatkan (sendirian) di salah satu sekolah co-ed yang cukup terkenal di Singapura, dengan fasilitasnya yang super lengkap. Saat orientasi dan berkeliling sekolah, saya membayangkan diri saya menikmati semua fasilitas sekolah tersebut selama setahun ke depan.
Di sekolah tersebut, saya berteman baik dengan dua orang, sebut saja L (laki-laki, asal Singapura) dan Z (perempuan, asal Tiongkok). Bersama mereka berdualah, saya belajar dan berpetualang lebih dalam seputar Singapura.
Pernah suatu ketika, saya mengajak mereka berdua datang ke tempat saya tinggal, lalu saat tengah mengobrol bersama mereka, saya nyeletuk ke mereka berdua, “kenapa, ya, kolam renang di sini jarang ada yang pakai?”
Mereka pun lantas menjawab dengan tegas: “tak ada waktu untuk itu.”
Saat itu, saya bingung mendengar jawaban mereka. Mengapa tak ada waktu? Kalau di Indonesia, kolam renang sebegini bagusnya nggak bakal dianggurin kosong begini. Kok, di Singapura bisa seperti ini?
Di akhir periode saya bersekolah di sana, saya pun akhirnya paham jawaban mereka berdua.
Ya, mereka tak ada waktu untuk itu. Tak ada waktu untuk bersenang-senang di negara ini.
Sekolah memang baru mulai pukul delapan, namun pukul enam, di saat langit Singapura masih gelap, siswa sudah mulai berdatangan. Mereka bersekolah sampai sore dengan berbagai macam materi pelajaran yang jauh lebih kompleks daripada materi pelajaran dalam negeri. Belum lagi tambahan kegiatan klub hingga malam bagi mereka yang mengikuti klub. Lalu, setelah kegiatan klub selesai, ada lagi les serta pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, serta belajar hingga dini hari, demi mengejar nilai sempurna. Begitu seterusnya. Berenang di kolam renang, bermain di taman, apa itu?
Selama setahun di sana, waktu bermain saya bisa dihitung dengan jari. Saya hanya sekali ke Sentosa (dengan Universal Studio-nya), sekali ke Merlion untuk foto-foto dengan L dan Z, dan dua kali ke Orchard Road. Saya lebih banyak menghabiskan waktu mengejar transportasi umum, di sekolah serta perpustakaan, dan sesekali ke Bras Basah untuk mencari art supply dan buku bekas. Hampir tak pernah terpikir di saya untuk bersenang-senang, apalagi berbelanja.
Lalu, warga Singapura pun tak seramah yang saya temukan di Changi Airport. Orang-orang di sana, terutama orang dewasa saat itu jarang saya lihat berekpresi. Ekspresi mereka datar. Mereka sibuk dengan dirinya serta kegiatannya masing-masing. Pengalaman saya yang berkesan di sana adalah saat saya pulang dari Bras Basah bersama Z dan kami kehujanan. Saat kami berdua meneduh, ada seorang bapak memberikan potongan karton untuk dipakai menggantikan payung. Lalu, saya bersama Z lantas berlari dengan karton di atas kepala, menuju halte bus. Keramahan yang jarang saya temukan di Singapura.
Lalu, setahun berjalan di sana dengan segudang pengalaman menyenangkan dan tak menyenangkan, tiba saatnya saya untuk kembali ke tanah air. Pengalaman saya saat di Singapura tak akan saya lupakan.
Terimakasih banyak.